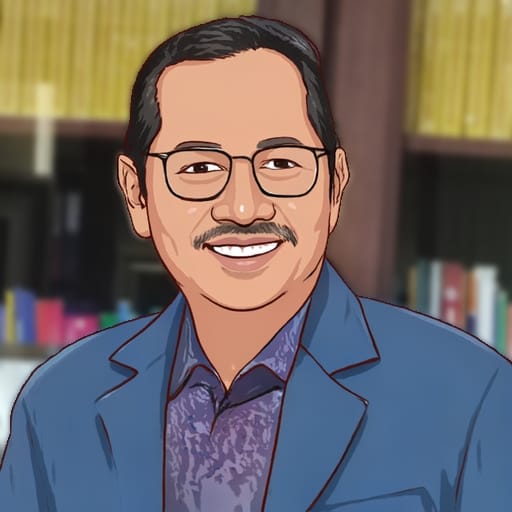
TRANSINDONESIA.co | Oleh: Muhammad Joni SH.MH.
Opini ini menolak negeri 062 retak. Kembalinya empat pulau—Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek—ke wilayah Provinsi Aceh melalui kesepakatan Presiden Prabowo, dua gubernur, dan Kemendagri pada 17 Juni 2025, adalah koreksi atas blunder administratif yang disebabkan lemahnya tata kelola birokrasi. Kasus ini menjadi preseden buruk dalam sejarah hubungan antarwilayah di Indonesia.
Dr. Chazali H. Situmorang, mantan pejabat tinggi negara—Sekjen Kemensos era Bachtiar Chamsyah, Deputi Kemenko Kesra, dan Ketua DJSN—serta alumni Universitas Sumatera Utara (USU), tampil sebagai suara yang kuat menjaga kebijakan publik yang tangguh.
Dalam esainya, bang Chazali menyebut tarikh ini sebagai “pembusukan dan pembiaran birokrasi.” Keputusan Kemendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan keempat pulau sebagai bagian dari Sumut, dibuat gegabah—berdasar dokumen fotokopi, tanpa upaya serius menelusuri arsip asli.
Sebagai birokrat profesional dan analis publik tangguh, Chazali menohok balik Mendagri Tito Karnavian dengan kalimat yang memantul di ruang logika: “Engkau yang memulai, engkau pula yang mengakhiri.”
Kritik ini tidak hanya administratif, melainkan berakar pada logika hukum dan etika pemerintahan.
Tiga Pelajaran Kunci
Pertama, kita menyaksikan kegagalan prinsip good governance. Kebijakan batas wilayah bukan sekadar urusan administratif, tapi berdimensi sejarah, identitas, dan sensitif terhadap kedaulatan lokal. Kecerobohan pengarsipan dan lemahnya verifikasi dokumen adalah bentuk abainya negara terhadap dasar legalitas yang sahih.
Kedua, meminjam kaca mata Critical Legal Studies (CLS) hukum pun demikian kebijakan itu mencerminkan bagaimana hukum dan regulasi tidak otonom. Namun tunduk pada kepentingan politik, instruksi sang kuasa, dan subordinasi malbirokrasi, lebih dari hanya maladministrasi. Seperti yang dicerminkan Bang Chazali, kebijakan bisa dibolak-balik sesuai suasana juncto selera, dan hukum pun menjadi alat bukan penjaga norma keadilan, kepastian dan kebenaran.
Ketiga, gimmick digitalisasi birokrasi kita ternyata masih goyah dan kosmetik. Pemerintah pusat bicara soal e-Government, tapi dokumen penting negara—yang seharusnya tersedia dalam sistem arsip digital nasional—justru hilang atau tidak (belum) ditemukan. Ini bukan semata soal teknis, melainkan kegagalan kultur tata kelola berbasis sistem.
Presiden Prabowo dan Kepemimpinan yang Merawat Jiwa Konstitusi
Dalam polemik yang berdimensi sengketa antar daerah yang sempat hendak disodorkan ke mekanisme gugatan tata usaha negara (TUN) ini, disadari efek panjangnya oleh Presiden Prabowo Subianto. Beliau tampil sebagai pengambil keputusan strategis yang tidak sekadar merespons kegaduhan sensitif bagi NRI, tetapi menunjukkan sikap kenegarawanan dalam mendengar suara kebenaran. Prabowo cermat membaca denyut jantung rakyat daerah, menimbang suara abadi sejarah, dan menempatkan konstitusi sebagai fondasi tindakan bernegara.
Prabowo tidak hanya bertindak sebagai perekat retaknya benteng birokrasi, tetapi juga sebagai penjaga semangat jiwa rakyat –Volksgeist— dan hapal sejarah lokal yang tak boleh dikalahkan oleh kesembronoan administratif.
Dengan sensitivitas kepemimpinan yang tajam terhadap isu-isu bersentuhan marwah daerah, Presiden 08 mengembalikan empat pulau ke pangkuan Aceh sebagai koreksi atas cacat kebijakan yang mengabaikan integritas sejarah dan enteng menjaga validitas legalitas fakta.
Dalam konteks ini, Prabowo menegakkan apa yang disebut leadership by truth: sebuah kepemimpinan yang lahir dari lantunan suara nurani rakyat, bukan sekadar kalkulasi kekuasaan dan kirka kepentingan kapital. Ia memperlihatkan bahwa menjaga NKRI bukan semata persoalan kokohnya benteng kua-geografis, tetapi juga menjaga memori kolektif dan keadilan historis.
Epilog: Kritik Cerdas dan Cermin Keadilan
Saya suka gaya kritik kebijakan publik ala Chazali Situmorang. Bagai memilik Kaca Benggala, esai-esai kebijakan publik bang CHS adalah cermin jernih yang reflektif terhadap wajah hukum yang tak netral a.k.a. otonom. Saya menduga dia akrab menggunakan pendekatan hukum progresif, membongkar lapis-lapis ilusi bahwa kebijakan kudu lahir dari nalar hukum yang otentik dan berkeadilan substantif. Dalam tradisi Critical Legal Studies, ia piawai mengingatkan bahwa “kebijakan dan hukum tak pernah bebas nilai— namun selalu dimuati kepentingan, kekuasaan, dan politik.”
Dengan kejernihan data, ketegasan logika, dan integritas moral, Bang Chazali tidak sekadar mengkritik birokrasi yang retak, tapi menuntut negara untuk kembali ke jalur integritas konstitusional dan keadilan kebijakan publik. Ia memberi contoh bagaimana kritik terhadap negara tidak berarti membenci negara, melainkan cara tertinggi untuk membela rakyat dan konstitusi. Kiranya begitu cara Bang Chazali mencintai Indonesia.
Presiden Prabowo tak cukup hanya memadamkan api; namun harus tuntas menelusuri sumber asap. Jika tidak, episode sengketa a.k.a pencaplokan wilayah, eksploitasi SDA, dan sabotase kebijakan publik hanya akan jadi pola baru dari patologi malbirokrasi gaya lama. Kepemimpinan konstitusional yang kuat dan berpihak pada kebenaran, seperti yang ditunjukkan Prabowo dalam kasus ini, menjadi harapan baru dalam menata ulang hubungan pusat-daerah secara adil dan berdaulat. Tabik. (MJ)





