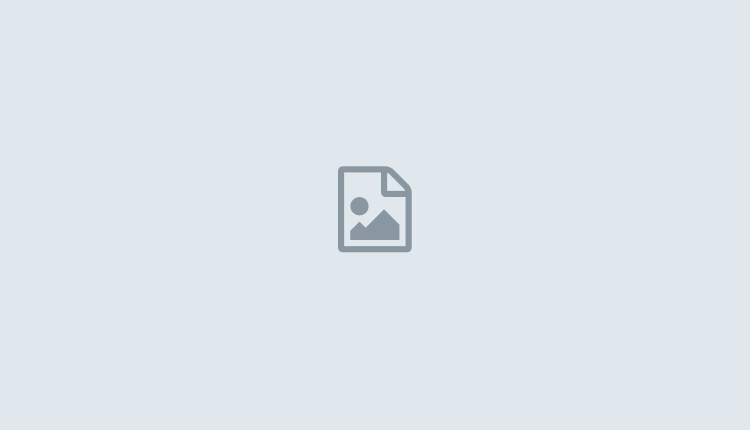TRANSINDONESIA.CO – Merasa bisa dan merasa berjasa itulah model-model keunggulan birokrasi patrimonial. Apa yang dikatakan baik dan benar menurut cerminnya sendiri, tiada lagi melihat manfaat dan kegunaan bagi banyak orang.
Marah bila ada yang menyatakan kebanaran, ‘buruk rupa cermin dibelah’. Marahlah kepada siapa saja yang mengusiknya, apapun dan siapapun dia akan dianggap sebagai kelompok galau, kecewa dan sakit hati, kepingin kebagian bahkan bisa saja dilabel sebagai penghianat.
Tatkala ditanyakan hasilnya atau kinerjanya maka akan memamerkan kemarahan-kemarahan dan sikap ketidak sukaannya.
Memamerkan apa yang dikerjakan walau tiada guna bagi masyarakat luas. Kalau ada juga tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.
Sikap hura-hura kerja secuil dengan biaya segudang menjadi kebanggaan, memanggil ndoro sana ndoro sini, sayang ini hanya seremonial dan hanya pada kepentingan-kepentingan narsis semata.
Ubyang-ubyung, regudag-regudug menjadi suatu unggulan bagai kaum kurowo menjilat sang Raja Astina, ‘duryudana’.
Semua merasa bisa, merasa berjasa, merasa penting dan memamerkan ini saya dekat di sana, dipakai di sini walau hanya mengisi absensi dan ide-ide copas (copy paste) semata. Tiada standar yang jelas, ide-ide copasan memang tidak salah namun itu bagai produk daur ulang yang tambal sulam serta ikut-ikutan atau menyenangkan ndoronya saja.
Ndoro ‘di sana-sini menang’, atau menang-menangan. Apapun keinginanya bagai sabda yang harus segera terlaksana, entah bgaimana caranya.
Semua pengikut-pengikut bagai brutus mengekor siap menerkam dan mengangkangi sumber-sumber daya.
Gaya dan ala mafia ini cepat atau lambat akan menimbulkan kebusukan-kebusukan dan pembangkangan sipil (civil disobidience).
Yang menjadi korban lagi-lagi adalah rakyatnya tiada lagi bisa memikirkanya. Gajah dengan gajah berkelahi pelanduk mati ditengah-tengah, ndoro merasa bisa dan menang-menangan rakyat menuai duka. (CDL-Jkt151215)
Penulis: Chryshnanda Dwilaksana