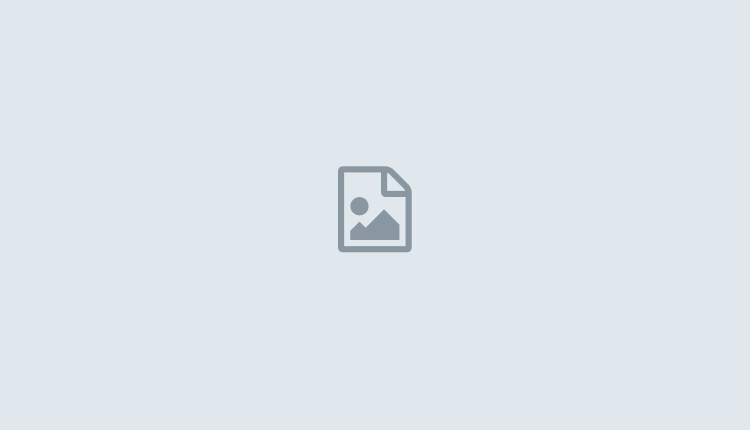TRANSINDONESIA.CO – Lulus dari Europese Lagere School (ELS), nasib buruk merundung Kartini. Ia harus menjalani pingitan. Keinginannya untuk melanjutkan sekolah ke Hogere Burger School (HBS) ditampik sang ayah, Bupati Jepara, Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat.
Usianya menjelang 13 pada 1892 itu. Mendadak, “Dunia Kartini menjadi sangat sempit, terbatas antara dinding-dinding gedung kabupaten yang tebal dan kuat, serta halaman yang luas dilingkari tembok tebal dan tinggi, dengan pintu-pintu yang selalu tertutup rapat,” tulis Sitisoemandari Soeroto dalam Kartini: Sebuah Biografi.
Ia pun harus belajar menjadi putri bangsawan sejati: bicara tak boleh keras; dilarang tertawa, hanya boleh tersenyum dengan bibir terkatup; berjalan perlahan-lahan; menundukkan kepala saban ada anggota keluarga yang lebih tua melintas.
Kartini marah. Kecewa luar biasa. Pada pagi hari, saat menyaksikan dua adiknya, Rukmini dan Kardinah, berangkat ke sekolah, Kartini kerap meneteskan air mata. Ingin rasanya ikut menghambur keluar, namun pintu segera tertutup untuknya.
Pingitan lazim dilakukan atas gadis-gadis ningrat. Menjelang remaja, mereka dianggap mesti menyiapkan diri memasuki kehidupan berumah tangga. Pingitan merupakan ‘sekolah’ untuk itu semua.
“…pola kehidupan gadis Jawa itu sudah dibatasi dan diatur menurut pola tertentu. Kami tidak boleh memiliki cita-cita. Satu-satunya impian yang boleh kami kandung adalah: hari ini atau esok dijadikan istri kesekian dari seorang pria!” tulis Kartini ke sahabat penanya di Belanda, Estelle “Stella” Zeehandellar.
Di rumah, Kartini coba curhat kepada 2 kakaknya, Sulastri dan Slamet. Tapi, sia-sia. Ketika Kartini menyinggung-nyinggung kebebasan yang dikecap para wanita seusianya di Eropa, Sulastri berujar, “Masa bodoh! Aku sih orang Jawa.”
Slamet dan Kartono
Sikap Slamet, sang kakak tertua, bahkan lebih buruk. Ia menganggap derajat Kartini lebih rendah. Maka, jika Kartini sedang duduk di kursi dan Slamet melintas, Kartini harus cepat-cepat turun, berjongkok, dan menundukkan kepala. Contoh lain, Kartini kudu berbicara dengan langgam Kromo Inggil (bahasa Jawa halus) kepada kakaknya itu.
Bentrok keduanya sering terjadi. Kalau ayah mereka ada di rumah, Slamet jeri bersikap keras. Sayangnya, Pak Bupati banyak berada di luar rumah. Slamet pun menjadi-jadi, sementara Kartini hanya bisa melawan dengan suara gemetar.
Namun, Kartini punya Kartono, kakaknya yang 2 tahun lebih tua. Dari Kartono, ia menerima buku-buku pemikiran modern. Misalnya tentang Revolusi Prancis. Sayang, Kartono tak setiap saat ada di sisi Kartini karena mesti bersekolah di HBS Semarang. Namun, tiap kali Kartono pulang ke Jepara, Kartini mendapat sosok yang bisa memahami jalan pikirannya.
Bacaan juga disediakan ayahnya: buku, majalah, dan koran berbahasa Belanda. Berkat pendidikan di ELS, Kartini bisa berujar bahasa Belanda dengan fasih. Juga mampu menulis dan membaca teks bahasa Belanda dengan lancar.
Semua bacaan itu lumayan menghibur Kartini. Wawasan dan pengetahuannya pun kian luas. Semakin sadar saja Kartini bahwa ada yang keliru dalam perlakuan terhadap kaum perempuan.
Setelah 4 tahun dalam pingitan, situasi mulai dikendurkan. Kartini, juga Rukmini dan Kardinah yang belakangan ikut dipingit, boleh sesekali ke luar rumah meski dengan pengawasan ketat.
Pada 2 Mei 1898, pingitan untuk 3 kakak-beradik itu resmi selesai. Mereka bertiga diajak ke Semarang untuk menyaksikan penobatan ratu Belanda, Wilhelmina. Kepada Stella, Kartini menulis, “Ini merupakan kemenangan yang sangat-sangat besar. Karena itu juga kami sangat menghargainya.”(sis)